|
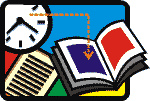 22/04
| Onoy memberi tahu, puisiku surat
hujan sudah dimuat di Cybersastra.
Dia bilang, "Sekarang Cybersastra lebih suka memajang nama
baru." Hehe, terhitung "nama baru" dong gua! 22/04
| Onoy memberi tahu, puisiku surat
hujan sudah dimuat di Cybersastra.
Dia bilang, "Sekarang Cybersastra lebih suka memajang nama
baru." Hehe, terhitung "nama baru" dong gua!
09/04 | Membalas email Agustinus Budiman. Kutulis antara lain:
"Tentang film kesukaan, ya hampir sama. Aku juga ingin memperluas khasanah dengan film-film non-Hollywood. Lumayan susah nyarinya, memang, atau lama nunggunya, tapi kalau dapat film yang kuincar-incar, wah puas banget. Hollywood yang
mainstream kurang asyik lagi. Aku malah suka cari yang kuno-kuno. Film bisu pun oke. Kalau aku ajak temanku nonton, mereka tanya, "Film tahun berapa ini, Mas? Hitam putih atau berwarna?" Aku bilang saja film abad ketujuh belas! Menurutku, film hitam putih tidak jarang justru lebih kaya daripada film berwarna. Bayangkan saja misalnya kalau
Schindler's List dibuat berwarna sepenuhnya, wah kurasa vulgar banget. Sebaliknya, ada materi-materi tertentu yang memang mau tak mau harus berwarna.
Raise the Red Lantern, misalnya, kalau hitam putih 'kan lucu.
Tarantino aku belum pernah ngicipi, justru film favoritnya yang sudah kutonton:
Chungking Express. Sedangkan Kurosawa, bagiku, ini sutradara yang karya-karya belum pernah kutemukan mengecewakan. Sejauh yang pernah kutontoh, semuanya bagus, atau malah istimewa. Tapi,
Dreams aku belum nonton. Karya dia yang masih kutunggu (belum ada di rental langgananku) adalah
Ikiru dan Throne of Blood."
08/04 | Membalas email Bung Saor. Kutulis:
"Sampeyan bertanya: Bagaimana pendapat Denmas dengan cerita-cerita yang mengungkap seks dengan agak vulgar begitu?
Topik menarik memang. Kalau secara pribadi, aku jengah. Bukannya sok moralis, cuma tahu diri saja....
Bukannya juga aku menentang adegan seks itu sendiri. Masalahnya adalah: Bagaimana seks itu digambarkan? Bagaimana implikasi moralnya? Salah satu penggambaran seks yang tender ya kurasa Jhumpa Lahiri itu. Sebaliknya, yang membuatku muak dengan telenovela, walaupun tidak menyajikan adegan seks yang vulgar, namun perselingkuhan digambarkan sebagai satisfying.
Contoh lain, bagian akhir Saman itu. Aku melihatnya sebagai ironi tragis orang modern. Mendiskusikan hal yang begitu intim (manusia adalah satu-satunya makhluk yang berhubungan seks
face to face) melalui jaringan internet, sebuah virtual reality.
Takaran-takaran semacam itulah yang membuatku justru agak "keberatan" dengan moralitas cerpenmu yang sebelum Ambarita (sori, fileku kabur; lupa judul dan tokoh-tokohnya). Aku melihat ketidakkonsistenan yang ganjil. Begini: Si pria dan si wanita teguh memegang komitmen mereka untuk tidak berpacaran, hanya bersahabat, sampai mereka lulus. Karena putus komunikasi, si pria akhirnya menjalin hubungan dengan wanita lain. Kemudian saat mereka bertemu lagi, mereka berpelukan (semalaman?) tanpa melakukan hubungan seksual. Aku menerimanya sebagai romantisme ala
A Walk in the Clouds (sudah pernah nonton?), dan kuanggap sebagai konsistensi mereka sesuai dengan komitmen sebelumnya. Namun, bangunan konsistensi ini ambruk pada
ending-nya. Si pria secara sepihak memutuskan hubungan dengan pacarnya untuk melamar wanita teman lamanya itu. Kenapa kukatakan tidak konsisten? Kalau dulu ia begitu teguh memegang janji selama masa kuliah (mengingatkan aku pada Mazmur 15:4b), lalu bagaimana sekarang dengan janjinya terhadap si pacar? Kalau aku jadi si wanita, aku akan berpikir dua kali untuk menerima lamaran si pria. Seorang pria yang seenak perut memutuskan hubungan dengan pacarnya, dengan alasan tersadar bahwa ia lebih mencintai teman lamanya, patut dicurigai niat tulusnya. Bagaimana kalau di depan nanti dia ketemu WIL lagi? (Bandingkan dengan A Walk in the Clouds: Paul Sutton membereskan dulu hubungannya dengan isterinya, baru ia leluasa mendekap Victoria. Makanya dalam My Valentine Flicks aku berkomentar: "Ajaib, moralitas masih diperhitungkan di perkebunan anggur eksotis ini!") OK, mungkin aku agak melantur. Aku rasa kalau mau menjadi penulis yang baik memang perlu juga membangun "teologi" yang sehat tentang bagaimana menempatkan seks (mungkin juga kekerasan dan omongan carut) dalam karya-karya kita. Aku ada dua artikel dari internet yang mungkin
relevan:
02/04
| Pax Xavier sepulang pelayanan dari Australia membawakan buku
terbaru Philip Yancey, Rumours of Another World. Sedap!
26/03
|
Wah, terus terang aku surprised dan lumayan "terpana" saat Bahana
menanggapi secara positif usulanku untuk meresensi X2. Mbak
Sari, sekretaris Bahana, memberitahukan via email:"Aku sudah bicara dengan Pak Otniel dan beliau
setuju untuk apresiasi kita mengangkat X-Men 2. Sepertinya untuk
Apresiasi, kita akan mulai mengangkat seni-seni kontemporer yang
lebih banyak menyentuh pembaca seperti X-Men itu." Resensiku
rencananya akan dimuat pada edisi Mei (capsule review-nya,
kalau bisa disebut begitu, bisa ditengok di daftar film
favorit kelompok #5).
Kurasa ini sejalan dengan yang telah kutuangkan dalam renungan Film. Kiranya kesempatan ini mengasah daya kritisku dalam "membaca" seni kontemporer, khususnya film.
05/03 | Aku menerima surat perjanjian penerbitan untuk Diciptakan dalam Sebuah Tarian Ilahi dari Yayasan ANDI. Wah, tapi revisinya malah belum sempat kugarap-garap juga....
13/02
| Menanggapi komentar rekan-rekan Penjunan atas Kado
Kejutan:"... Beberapa rekan menyarankan saya untuk "merenyahkan" cerpen remaja itu dengan menggunakan bahasa gaul. Untuk itu, saya ingin memberikan catatan kecil
(semacam "pembelaan", hehe):
- Saya tidak menulis dalam bahasa gaul terus terang justru karena saya tidak menguasainya. Saya hanya mengerti sekilas-sekilas. Hampir seperti bahasa Jawa: untuk membacanya, saya masih bisa (saya
enjoy membaca GFresh!); namun, kalau mesti mengungkapkan pikiran dan perasaan saya
sepenuhnya dalam bahasa tersebut, wah, saya angkat tangan. Nanti malah tulisan saya jadi tidak wajar, tidar jujur. Kalau tidak, ya saya mesti belajar dulu berbahasa gaul "yang baik dan benar" (Mbak Ita bisa ngajari?
Brekele itu opo sih mangsudnya? 8-)).
- Saya tidak menulis dalam bahasa gaul karena saya mencoba menerapkan 'kaidah' penulisan cerita yang baik. Seorang penulis menyatakan, "Pengarang pemula juga sering bingung menempatkan bahasa pop, slank atau dialek dalam cerpennya. Kalimat-kalimat tersebut tak jarang diletakkan dalam paparan narasi. Padahal kalimat-kalimat narasi seharusnya menggunakan bahasa yang standar, baku dan berlaku umum. Boleh saja kita menggunakan bahasa slank, pop atau dialek, tetapi terbatas pada dialog antartokoh, guna memperjelas warna lokal dan karakter
tokoh."
- Saya tidak menulis dalam bahasa gaul karena saya berharap tulisan-tulisan saya 'abadi.' Bukankah bahasa yang standar relatif akan lebih awet?"
12/02
| "Nah, aku sudah pulang," kata Sam di ujung petualangan
Persekutuan Cincin di Dunia Tengah. Ya, rampung sudah pembacaan
pertama The Lord of the Rings yang penuh detil gambaran
lokasi dan petualangan menggigilkan. (Namun, berbagai
apendiksnya yang seratus halaman lebih itu baru kubuka-buka
sedikit.) Tinggal tunggu filmnya -- semoga Mataram memutarnya
tidak terlalu lama setelah main di (syukur-syukur malah
berbarengan dengan) Jakarta. 05/02
| Mendapatkan tugas baru dari Majalah Bahana. Mulai bulan
ini, untuk sementara aku diminta menjaga gawang rubrik
"Citra" (biografi tokoh Kristen).
03/02 | Menikmati "Laba-laba,"
kumpulan cerpen Gus tf Sakai. Wah, imajinatif sekali, dan
bahasanya pun terolah dengan baik dan indah. Latarnya bukan cuma
Padang, namun juga NTT, Toraja, Papua, dsb. Bagaimana observasinya,
ya?
29/01
| Membalas email Slamat P. Sinambela, mengulas cerpennya Huta
Ginjang:
"Yang harus kupuji tentu saja memorimu yang kuat, sehingga aku merasa ikut diajak mendaki ke sana.
A good description! Babi-babi yang berdesakan itu -- rasanya bau anyirnya pun bisa tercium. Bagaimana ini pengolahannya -- sampeyan membuat catatan harian, mengandalkan kenangan dan imajinasi, atau malah hanya mendengar cerita orang?
Sayangnya -- hehe, ini nggak enaknya -- sampeyan masih gatal untuk menjelas-jelaskan, merasa kurang yakin kalau pembaca bisa menangkap maksud Anda dan menyimpulkannya sendiri. Perhatikan ini: "Kemiringannya membuat kami harus mendaratkan pantat berulangkali, karena terlalu lelah." Tidakkah sampeyan percaya bahwa pembaca akan mengasosiasikan "mendaratkan pantat" dengan "lelah" tanpa mesti dieksplisitkan seperti itu. Dengan kata lain, anak kalimat "karena terlalu lelah" tentunya bisa ditanggalkan saja.
Juga, aku merasa mak cleguk saat Anda menutup paragraf kedua dengan: "Sebuah pemandangan yang langka aku dapati." Tanpa Anda sodorkan kesimpulan itu, benak pembaca
sebenarnya sudah tergoda untuk berkomentar, "Asyik juga tempat ini!"
Kekurangan kedua, latar yang bagus itu baru tampil sebagai latar fisik, belum menjelma menjadi sebuah latar budaya. Maksudnya, cerpen sampeyan tidak berkembang menjadi konflik "manusia versus alam," misalnya, padahal pokok persoalan yang Anda sodorkan (dampak posmodernisme), rasanya menarik kalau diberikan suatu contoh kasus dari Huta Ginjang. Seandainya tidak ada dialog soal posmo itu, rasanya seperti sedang membaca laporan perjalanan di
Kompas Minggu itu.
Kekurangan paling menonjol berkaitan dengan kekurangan di atas. Tidak adanya contoh kasus berarti Anda tidak mempertontonkan
(showing), bagaimana sih kira-kira dampak posmo di sebuah desa semacam Huta Ginjang. Tema itu hanya dijadikan bahan dialog, itu pun kedua pihak yang berdialog (Ompung Jumitro dan Wisnu) sama-sama alergi pada posmo. Hehe, seharusnya sampeyan menulis esei Bung Slamat..... Pernah membaca
Burung-burung Manyar-nya Y.B. Mangunwijaya? "Kegagalan" novel ini juga sama. Temanya tidak diolah dalam bentuk cerita, namun dikhotbahkan melalui pidato Larasati saat menerima gelar doktor. ("Penyakit" novel-novel Romo Mangun memang di situ. Yang kurasa paling berhasil sebagai cerita, yang paling
showing, adalah Romo Rahadi. Penyakit serupa juga dapat dijumpai pada STA -- karyanya yang
showing justru karya-karya awalnya, seperti Anak Perawan di Sarang Penyamun. Layar Terkembang dan seterusnya terlalu dibebani ide filsafat. Yang kurasa paling berhasil memadukan cerita dan ide ya Pramoedya Ananta Toer dengan tetralogi Pulau Burunya itu -- ceritanya benar-benar
menyedot!)" 26/01 | Yayasan ANDI memberikan lampu
kuning untuk naskahku Diciptakan dalam
Sebuah Tarian Ilahi. Mereka memintaku mengeskplorasi lagi
sejumlah poin, memfokuskan sasaran pembacanya (kaum wanita, remaja
dan dewasa muda), dan menajamkan gayanya sesuai dengan sasaran
pembaca tersebut (kira-kira dengan jurus jurnalisme sastrawi itu).
Aku disangoni Tak Enteni Keplokmu: Tanpa Bunga dan Telegram
Duka-nya Sindhunata untuk perbandingan.
01/01 | Selamat tahun baru!
|