Dilema Produk Bajakan
15/04/2004
Seorang teman melontarkan pertanyaan telak
padaku: "Apa mas tidak terbebani secara moral untuk menonton film vcd hasil copy dari
dvd?"
Sebelum berkomentar lebih jauh, saat memikirkan pertanyaan itu, sempat terpikir, kenapa pertanyaannya tidak lebih menonjok lagi: "Apa mas tidak merasa berdosa menonton vcd bajakan?" Hehe.... (Atau: istilah "dosa" sudah kurang populer lagi, ya?)
Dulu saat gencar-gencarnya sweeping produk bajakan, aku sempat berniat untuk tidak meminjam vcd salinan dvd lagi. Nyatanya, niat tinggal niat. Saat film-film bagus bermunculan, hm... mana tahan. Sudah begitu, aku merasa tertolong dengan Pasal 15 butir d Undang-undang HAKI: "Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya." Ya, anggap saja rental langgananku itu "perpustakaan umum"; dia punya produk originalnya, dan memperbanyak terbatas untuk disewa anggotanya.
Okelah, aku tahu itu semua bisa dibilang akal-akalan, upaya konyol untuk menutup-nutupi dosa covetousness alias menginginkan apa yang bukan haknya; dengan kata lain, tidak puas dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki (Kalau belum punya DVD player, ya ndak usah kepengin nonton DVD, begitu). Dalam tataran moral, kondisi ini mirip dengan pengalaman nabi Yesaya: "Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang pembajak, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa pembajak" (sori, saya "tafsirkan" ulang).
Dalam tataran praktis tingkat pribadi, lebih rumit untuk bersih dari pembajakan. Di luar hitung-hitungan moral, kurasa alternatifnya hanya dua:
Pilihan pertama, kita cukup kaya dan cukup cermat untuk hanya mengkonsumi produk-produk original. Kaya saja terbukti tidak cukup, karena orang kaya yang mestinya mampu membeli produk original, namun entah kenapa toh melirik juga produk-produk bajakan. Sedangkan masalah cermat, rumit lagi. Komunikasi kita via internet ini saja, misalnya, seberapa jauh bersih dari produk bajakan? Software-software yang kita pakai, original semua? Contoh lain: membeli buku terjemahan, eh ternyata penerbitnya tidak membayar royalti pada pemegang hak ciptanya, bagaimana itu? Bukunya termasuk produk bajakan atau bukan? Dan seterusnya.
Pilihan kedua, kita pindah ke negara yang bersih pembajakan, serta menjadi warga negara yang patuh di situ. (Ini sudah kembali ke masalah moral; kalau mentalitasnya pembajak, di negara "bersih" pun kita akan membajak.)
Begitulah, mau tidak mau, besar atau kecil, kita memang mesti ikut menelan "dosa kolektif" bangsa ini. Dalam taraf pribadi, yang bisa kuusahakan adalah seminimal mungkin mengkonsumsi produk bajakan; dan kiranya dijauhkan dari memproduksi produk bajakan.
Rekan-rekan punya perspektif lain untuk dilema ini, baik dalam tataran moral maupun tataran praktis? Kutunggu!
Bisa juga kirim email ke [email protected].
Sebaiknya diketik dulu offline, baru diposkan.
Tanggapan akan diedit seperlunya untuk pemuatan. Trims!
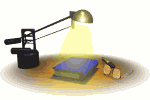
06/05 | Agustinus Budiman (Medan):
aku setuju dengan pendapat mas... memang kita semua tak akan pernah bersih dari kesalahan, sekalipun itu hanya noda-noda kecil.
aku tak tahu harus memberikan pendapat apa, tapi ya menurutku ini masalah untung rugi saja. produsen original nggak senang hasil produksinya dibajak, karena pasti keuntungannya akan berkurang. sementara produsen bajakan adalah orang2 yang berusaha untuk bertahan hidup.
tapi tentu saja kita tak boleh selalu menganggap produsen sebagai orang yang dirugikan. bisa jadi produk mereka memang kurang berkualitas, atau mungkin harga yang masih terlalu mahal untuk ukuran kantung orang indonesia, atau karena produknya memang kurang lengkap.
[Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan]
16/04 | Purnawan Kristanto (Yogyakarta):
[Catatan: Email tanggapan ini ditulis menggunakan program Windows bajakan dan dikirim dengan software Outlook Express bajakan pula. Mohon maaf untuk Mr. Bill Gate kalau ikutan mbaca email ini]
Sebagai seorang penulis buku, saya masih terngiang-ngiang Golden Rule yang dikhotbahkan oleh pak Martin Muslie, pada ibadah pagi sebelum kerja. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" kata pengkhotbah. Kalau kamu pingin orang lain bermurah hati kepadamu, maka bermurah hatilah dulu pada orang lain. Kalau kamu tidak ingin buku hasil tulisanmu dibajak orang lain, maka kamu jangan membajak karya orang lain. Kalau kamu tidak ingin rejekimu (royaltimu) dicuri orang lain, maka kamu jangan merampas rejeki orang lain. Demikian kira-kira kalau diterjemahkan dalam konteks penulis.
Tetapi kemudian saya mendapat petunjuk dari teman, dalam hal penggunaan software komputer (atau teknologi canggih lainnya), hukum ini hanya berlaku kalau keadilan sudah terjadi di dunia. Kenyataannya, ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara di dunia ketiga semakin dalam dan curam saja. Sungguh ironis mengingat resources dunia ini sebagian besar diboroskan oleh dunia maju. Negara maju yang penduduknya hanya sepertiga penduduk dunia, menghabiskan sebanyak dua pertiga sumber-sumber alam yang ada di dunia ketiga.
Dalam perspektif teori tanggung jawab dan etika sosial, mestinya dunia industri di negara maju punya kewajiban moral untuk melimpahkan kembali resources yang telah mereka sedot itu. Istilah populernya, "pemerataan rejeki" lah. Tapi hal ini belum memuaskan. Sampai sekarang pun dunia-dunia Barat masih enggan untuk melakukan alih tegnologi pada dunia ketiga. Mereka juga terkenal pelit untuk bagi-bagi ilmu mereka. "There is no such free lunch, man" kilah mereka. Dengan penguasaan tegonologi ini, pengurasan sumber-sumber alam sdi dunia ketiga emakin dipercepat dan semakin masif lagi.
Dalam ilmu politik dikatakan, siapa yang menguasai sumber-sumber kehidupan (resources), maka dia mempunyai kekuasaan. Semakin besar atau semakin langka resources yang mereka kangkangi, semakin besar pula kekuasaannya. Secara de Facto, dunia ini sudah "diperintah" oleh negara-negara industri. Celakanya, karena perbedaan ketimpangan ini, negara-negara maju ini bisa seenaknya menetapkan aturan yang kelihatannya "demokratis", tetapi sebenarnya merugikan negara miskin dan semakin memperbanyak pundi-pundi uang mereka. Sebagai contoh, kesepakatan WTO/AFTA/NAFTA yang dipropagandakan sebagai sistem yang saling menguntungkan, sebenarnya tidak lebih sebagai upaya negara maju untuk membelah benteng pertahanan pasar-pasar lokal di negara miskin. Mereka ingin memasarkan produk mereka secara bebas ke negara ketiga yang belum bisa memproduksi produk sejenis. Ironisnya, kadang produk itu menggunakan bahan mentah yang dikeduk dari dunia ketiga.
Kaitannya dalam Intelectual Property Right, pernahkah terpikirkan di benak teman-teman, siapa sih yang merumuskan isinya? Siapa pula yang paling gencar menyuarakannya? Apakah niat mereka itu tulus, atau karena mereka punya kepentingan tertentu di dalamnya? [Menurut kabar burung, konon operasi pemberantasan VCD bajakan di Indonesia disponsori oleh Asosiasi Perfilman Amerika. Sedangkan operasi software bajakan juga didanai oleh Microsoft]
Jangan salah sangka! Saya tidak menolak adanya penghormatan terhadap HAKI. Saya sangat setuju. Namun yang perlu dicermati adalah apakah isinya sudah mencerminkan keadilan atau belum! Sebagai contoh: Karena ketiadaan dana dan fasilitas untuk riset, akhirnya banyak sekali karya-karya lokal, hasil karya nenek moyang Indonesia telah dipatenkan oleh bangsa di luar negeri. Kabarnya cara pengolahan tempe sudah dipatenkan oleh bangsa lain. Jadi nanti jangan heran kalau kita ingin mendirikan industri tempe, maka kita harus membeli hak wara laba (franchise) dari bangsa lain. Lalu bagaimana dengan nasib warisan jamu dan cara pengobatan tradisional Indonesia? Bagaimana pula dengan hasil kearifan lokal (local wisdom) lainnya yang karena ketiadaan catatan, kita tidak bisa menelusuri siapa pencipta aslinya? Jangan-jangan, karakter Punakawan pun nanti juga dipatenkan bangsa lain.
Ini menjadi dilematis. Ambil contoh dalam program komputer. Jika kita harus membeli produk asli, maka ketertinggalan bangsa Indonesia akan semakin jauh. Saya membayangkan mungkin komputer akan menjadi aset yang sangat berharga sehingga harus dijaga oleh satpam siang dan malam. Di sisi lain, memang memakai produk bajakan itu adalah tindakan yang kurang bermatabat. Maka, solusi paling sederhana adalah memakai software versi lama yang masa hak ciptanya sudah kedaluwarsa. Memang kurang bergengsi, namun yang penting kita masih bisa memakai fungsi utama program itu. Kadangkala kita menjadi korban dari "kelicikan" produsen software komputer. Secara berkala mereka mengeluarkan versi terbaru dari sebuah program dan membujuk kita untuk selalu mengupdate program terbaru. Padahal seringkali tambahan yang dipromosikan oleh produsen itu bersifat artifisial saja. Kebanyakan tambahan itu hanya untuk menambah kenyamanan pemakaian. Sebagai contoh, sampai sekarang saya masih memakai Outlook Express versi 4, yang kalau orang Amerika tahu mungkin saya digolongkan dengan Flinstone. Tapi toh saya puas memakainya. Ketika tahun kemarin saya main ke kantor redaksi harian KR, saya melihat ada wartawan yang masih mengetik memakai program WS (Wordstar) versi 5. Di kantor BAHANA, masih ada juga komputer yang memakai Windows 3.11 (Yang kalau ingin menjalankannya harus mengetik "Win" di prompt DOS, lalu "Enter"). Toh, mereka bisa bekerja dengan optimal.
Nah, kalau VCD atau DVD saya cenderung berpendapat itu bukan kebutuhan yang urgen. Kalau saya sih memilih untuk membeli produk aslinya. Kalau tidak punya uang untuk membelinya ya cari hiburan lain saja, daripada berbuat dosa. Atau kalau mau bersabar, ya nunggu diputar di Televisi saja.
Di atas semua itu, yang lebih penting adalah mengkritisi UU Hak Cipta. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif. Kita tidak bisa bersikap tidak peduli dengan berkata, "yang penting saya tidak memakai produk bajakan". Sikap seperti ini hanya merupakan kesalehan semu, sebab bersikap tidak peduli pada situasi ketidak-adilan.
[Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan]
16/04 | Hendro Nugroho (Provo, Utah, AS):
Kalau Mas Ari mengupas masalah CD/VCD/DVD bajakan, saya akan
berkomentar masalah sofware komputer. Intinya tetap sama: pembajakan merupakan dilema bagi sebagian besar dari
kita.
Saya teringat ketika Bola dan Esther datang ke Jogja dan mulai
mengajarkan untuk taat pada pemerintah (secara sederhana: kalau naik
motor ya harus punya SIM, etc.) dan untuk tidak memakai produk bajakan.
Waktu itu Bola dengan bangga menunjukkan sertifikat windowsnya dari
Microsoft dan saya hanya bisa mringis (setengah tersenyum dan kepingin). Bagaimana
tidak, pada waktu itu, praktis hampir semua produk komputer yang saya pakai adalah produk bajakan kecuali satu software yang saya minta ijin secara resmi untuk saya pakai mengerjakan skripsi
(ironisnya, program itu dibajak beramai-ramai,ketika saya pinjamkan ke teman-teman di geografi).
Ketika sampai di Amerika, saya dapati bahwa produk-produk itu harganya
mahal (bahkan untuk ukuran orang Amerika) dan teman-teman saya di sini
tidak 'rakus' akan barang bajakan meskipun kalau mereka mau, akan mudah
mendapatkannya. Kalau tidak punya, tidak mampu beli, mereka tidak mau
pakai.Sebagai kompensasi akan pemenuhan kebutuhan mereka akan software,
mereka tinggal di kampus lebih lama (seringkali sampai jam 2 dini
hari!)
Di BYU saya sewa komputer sekaligus bayar 'high-speed' internet
connection sebesar $22.30 per bulan. Di komputer yang saya sewa itu
hanya terpasang Windows dan Microsoft Office (tanpa Microsoft Access &
Front Page). Tanpa software kesukaan lainnya. Rasanya kenyamanan yang
saya nikmati sebelumnya terbelenggu.
Dua tahun lalu ketika hendak berangkat ke MIT, saya membeli laptop.
Pilihan jatuh pada Thinkpad yang punya keyboard empuk dan bundel
software kas (semasa SMA, diam-diam IBM jadi favorit/impian(?) saya).
Pertama kali saya punya software resmi dengan sertifikatnya (:-)).
Karena perangkat lunak yang bakal saya pakai untuk thesis harus
dipasang pada OS Unix atau variannya, akhirnya saya pasang Redhat (mrpk. hadiah
natal: buku dan CD-resminya dari prof.) di laptop itu, sekarang jadilah
dual booting OS.
Saya sangat kaget ketika laptop itu dipakai guru saya di MIT. Jarinya
yang besar-besar itu menari di atas keyboard, mengetikkan
perintah-perintah pada terminal gnome, dan komputasi rumit berjalan
sangat cepat dan selesai! Wow! Saat itulah mata saya benar-benar
terbuka, bukan perkara apa, tetapi di tangan siapa.
Mulai saat itu saya mendalami linux dan membuat komitmen: kalau bisa
memakai barang legal, gratis, dan dapat menyelesaikan tugas kita,
bahkan lebih 'ampuh,' mengapa harus membajak?
Saya lontarkan gagasan saya ke milis Eks Keluarga Mahasiswa Kristen Fak
Geografi UGM. Seru jawabannya! Mereka beramai-ramai menolak gagasan
saya dengan alasan bahwa Windows adalah produk kapitalis dan sah-sah saja
memakai produk bajakan itu. Lebih jauh, mereka menganggap saya pro
Amerika, condong pada kaum kapitalis. Sebagai tentangan mereka juga
menyerukan: Hidup Grogol! beberapa minggu kemudian, sweeping CD bajakan
di sana...
Saya menyerah di komunitas itu, tetapi tetap pada komitmen saya.
Setelah merasa terbatas dengan dual booting, saya melakukan migrasi penuh ke
Redhat Linux dan sampai hari ini oke-oke saja, malahan saya menemukan
banyak hal baru yang mengasyikkan.
Kalau IBM merogoh koceknya sebanyak 1,2 billion dollars supaya semua
mesinnya bisa dipakai untuk Linux, mengapa saya enggan memakainya
secara cuma-cuma? Salah seorang teman di Jerman bilang: miskin kok boros!
Saya percaya bahwa setiap kita bisa membuat komitmen untuk tidak
membajak. Bekerja dengan barang resmi itu melegakan dan jauh dari
kutuk.
Saya punya teman Indonesia yang tinggal di sini, tetapi kesukaannya
masih tetap sama, yaitu mencari barang bajakan. Saya pikir: untuk apa
semua itu? Apa yang dihasilkannya? Nothing! hanya kotak katik software
ini, software itu. Tanpa MSWord pun Musa sanggup menorehkan Firman
Allah dan mewariskannya untuk kita bukan?
Teringat ketika semua orang mengutuki Soeharto sebagai koruptor,
ternyata kenek bus kota di Jogja pun mengkorupsi uang para mahasiswa,
pasalnya ia tidak mengembalikan Rp 50 dari Rp 200 yang dibayarkan
(waktu itu tarif bus kota untuk mahasiswa Rp 150). Ketika kerja di UPN saya
melihat uang $5000 (waktu itu kursnya Rp.12500) tinggal $500 tanpa bisa
berteriak dan 300 juta rupiah lainnya menguap.
Lha apa kaitannya dengan dunia pembajakan? satu hal berkaitan dengan
hal lainnya dan terbentuklah rantai, sering disebut sebagai lingkaran
setan. Untuk memutuskan lingkaran setan, haruslah dimulai dari diri kita,
siapa tahu kita adalah salah satu mata rantai setannya!
[Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan] Seperti telah saya sampaikan dalam email saya sebelumnya bahwa email
saya berikutnya adalah tentang pengalaman pahit dibajak dan menggunakan
produk bajakan.
Kelas 1 SMA adalah waktu pertama kali saya memakai komputer. Kebetulan
sekolahan saya punya tiga komputer, satu komputer machintosh dan dua
ibm kompatible. Waktu itu program-program belum semenarik sekarang dengan
warna-warni dan grafik yang memukau. Setiap kali komputer dinyalakan
prosesornya harus melakukan komputing rom-nya yang hanya 512kb
(bandingkan sekarang 64MB-2GB). Hardisk pun belum ada. OS dan program
(lotus atau wordstar 3.0) tersimpan di floppy disk besar (saya lupa
ukurannya).
Setelah menang pada tes komputer se-Solo (pesertanya sekitar 40 orang
:-)) saya dapat kursus gratis 1/2 tahun di IMKA dan membawa 2 guru
untuk kursus gratis masing-masing selama 1/2 tahun. Mulailan saya mengenal
dunia komputer.
Tahun-tahun pertama komputer masuk Indonesia, belum banyak produk
bajakan. Kalau orang beli komputer (IBM kompatibel), vendor akan
memberikan DOS, bahasa pemrograman BASIC, dan beberapa software untuk
keperluan kantor berikut buku-buku panduannya yang cukup tebal.
Semuanya tertera pemilik lisensi. Begitu komputer mulai bertambah banyak.
Pengkopian program pun semakin marak. Mungkin kasusnya sama dengan VCD.
Program-program yang saya pakai ditempat kursus pun dikopikan oleh guru
dari program-program hasil pembelian komputer di situ.
Pada waktu itu saya sempat mempelajari pemrograman basic dan
interpreter bahasa mesin memakai hexadesimal dan binary.
Akhirnya saya mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh program sewaktu
ia sedang berbicara dengan mesin dan memberikan perintah kepada kotak
bodoh itu. Wah, kalau perintah-perintah itu saya terjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, pasti bagus deh, pikir saya. Dan mulailah saya
melakukan hacking kecil-kecilan dan memodifikasi perintah-perintah DOS
ke dalam bahasa Indonesia. Hari-demi hari pengkodean berlangsung,
mengubah bahasa manusia ke bahasa mesin ternyata memakan waktu. Kurang
lebih seminggu, rampung sudah komentar-komentar DOS dalam bahasa
Indonesia. Itu pun ditambah dua malam saya menginap di rumah teman
supaya dapat memakai komputernya.
Hari-hari di lab IMKA pun saya lalui sampai pada suatu ketika kotak
Disket saya dipinjam teman. Hari berikutnya DOS terjemahan itu sudah
beredar... Mangkel rasanya, kerja keras dikopi begitu saja.
Tahun berganti tahun. Saya sampai ke UGM dan tibalah waktu mengerjakan
skripsi. Komputer saya hilang dicolong maling ketika pindah kos. Saya
nego dengan kakak angkatan untuk boleh memakai komputer dan
software-nya. Semua syarat yang diminta sudah saya penuhi, ternyata
'nggih ra kepanggih' (bilang ya cuma bo'ong doang ;-)). lha
dalah.. kayak bayar upeti ke pemungut cukai!
Ketika hendak mengerjakan skripsi, saya mengontak vendor Research
System dan menerima kode untuk perangkat lunak mereka. Hanya saja saya belum
punya komputer waktu itu. Sewaktu sedang menunggu dosen pembimbing saya
bertemu mahasiswa S2 penginderaan jauh. Omong-omong akhirnya sampai
pada kesepakatan untuk barter. Ia punya komputer tapi tidak punya perangkat
lunak dan saya sebaliknya. Saya pun ke kos-kosannya,dan mulai memasang
perangkat lunak itu, dengan harapan dapat segera mengerjakan skripsi.
CD saya tinggal di rumahnya dengan asas kepercayaan. Lain hari saya dapati
para mahasiswa pasca sarjana geografi pada pakai program itu dan ketika
CD saya minta, ia bilang CD sedang dipinjam teman-temannya! Setiap kali
saya ke situ, ia malah sedang asyik pakai komputernya untuk mengerjakan
thesis, walah...jatuh ke mulut buaya.. (untunglah waktu itu komputer Yanti-Eki boleh dipakai..ahh!)
Setelah lulus UGM, saya mengajar anak-anak S2 yang pengin tahu software
yang akan mereka pakai untuk thesis itu, dibayar 200 ribu sebulan! Di
Amerika, untuk belajar software itu orang harus bayar $1000 dolar per
hari + menanggung ongkos pesawat dan penginapan gurunya!!
Weleh..weleh...
Ketika saya simak banyak hal yang menimbulkan kekecewaan,dan sakit hati
dan kesialam itu ternyata kalau dipikir-pikir layak saya
terima. Pembajak kok nggak mau dibajak. he..he..he. Demikian juga dengan penghargaan
yang tidak semestinya akan kemampuan yang kita miliki. Hah!
Karena itulah saya lega sekarang. Hidup lebih produktif dengan produk
legal yang gratis! (Saya tidak mau spent lebih dari $100 untuk windows
+ beberapa ratus dollar lagi untuk MS Office); cukup 3 dollar dapat linux
+ open office/star office (yg kedua gratis krn mahasiswa) + semua
bundle software yang ada.
Memang 'Umat-Ku binasa karena tidak berpengetahuan!' begitu firman Tuhan.
[Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan] 16/04 | Cipto Wijoyo (Jakarta):
Saya ingin mulai dari hukum ekonomi terlebih dahulu...... "Ada pembeli ada penjual". Barang bajakan akan selalu ada dikala angka keinginan terhadap produk tersebut masih tinggi. Hukum permintaan dan penawaran kembali membuktikan dirinya.
Mari kita lihat kebelakang sejenak. Ketika VCD bajakan masih berada di posisi Rp. 13.500,-, produk original keluar dengan harga berkisar Rp. 39.000,- hingga Rp. 59.000,-. Pada saat VCD bajakan mulai menyentuh angka Rp. 9.000,- per film akibat pergeseran sosial dan koneksitasnya dengan hukum yang saya sebut diatas, saya rasa original masih belum menunjukkan perlawanan dalam harga. Mungkin hanya beberapa item yang akan di beri diskon khusus dan di toko tertentu pula. Yang menakjubkan, ketika Undang-Undang HAKI di berlakukan. Distributor lokal di Indonesia seakan mendukung total keberadaan hukum tersebut. Vision yang memegang lisensi Walt Disney, Warner Bros, dan beberapa studio independent lainnya, membanting harga hingga Rp. 15.000,- untuk semua film-film yang memiliki umur produksi cukup lama. Yang lainnya tentu tidak mau kalah. Dutamitra, pemegang Tristar Columbia Home Video. MediaLine untuk sebagian besar Universal Studio. MovieLine untuk Paramount Picture. Semuanya mereduksi VCD Original mereka hingga Rp. 17.500,-. Kemudian disusul oleh Musica Video Van pemegang lisensi Twentieth Fox termasuk beberapa film Metro Goldwyn Meyers dan Canal+ Distribution. Rasanya masih belum cukup melihat sepak terjang original melawan bajakan. CCJ/Hypermedia dan Emperor Optical Disc yang memiliki produk untuk rumah produksi menengah di luar sana, cuci gudang hingga Rp. 10.000,-. Tower Movie Entertainment juga ikut ambil peran, pemegang sebagian besar nama Miramax ini mensejajarkan posisi dengan rekan distributor lainnya. Jika Anda yang masih rajin ber-gerilya ke toko-toko film di Mal atau Plaza saat ini. Akan ditemukan film-film dari distributor yang saya sebutkan diatas, masih ada dan masih bercokol dengan harga yang boleh dikatakan cukup murah. Apalagi belakangan ini, BlockBuster Entertainment yang dikenal dengan koleksi-koleksi film-film Mandarin, Jepang, Korea dan beberapa dari Thailand ini mulai menurunkan harga hingga Rp. 12.500,- perfilm.
Namun teman-teman, seperti yang kita tahu bersama........ berapa harga VCD bajakan saat ini? Rata-rata Rp. 3.500,- per film atau Rp. 10.000,- per tiga! Gila kan? Sampai kapan mereka akan meng-adu angka? Kita baru membicarakan VCD!!!! Belum DVD!!! Hal inilah yang saya sebut dilematis dan ironis nya keadaan.
Yang bisa dijadikan pertanyaan :
Jika ada pertanyaan beban secara moral ataukah tidak, Saya rasa kita perlu lebih jauh mendefinisikan apa moral itu sendiri? Seberapa berat kadar moralitas bisa diukur? Apakah saya sebagai umat beragama kemudian mengkonsumsi bajakan akan membuat moral saya berkurang? Atau jika saya tidak mengkonsumsi bajakan sama sekali tapi saya juga tidak melakukan ibadah dengan baik, apakah hal ini akan membuat saya lebih ber-moral?
Saya pribadi tidak akan munafik. Saya pengkonsumsi 'kuat' produk-produk bajakan. Apalagi akhir-akhir ini saya menemukan cukup banyak film-film bagus kelas dunia maupun festival yang tidak hadir dalam bentuk Original. Tapi itu hanya sebatas rental atau pinjam. Karena saya masih berpegang teguh dengan pendirian untuk hanya tetap mengoleksi produk Original. Saya bersyukur karena sejauh ini masih kuat menghadapi cobaan yang kian hari kian menekan itu. Sangat saya yakini, kesenangan akan film memang sesuatu yang mahal harganya - dalam arti harfiah ataupun tidak. Hingga ketika saya memiliki sebuah film yang paling saya inginkan dan itu produk legal....... wow, tidak terhitung tingginya angka kepuasan yang saya dapatkan. Melihat benda tersebut tertata rapi di lemari saja sudah mendatangkan rasa
tentram....
piracy is a crime....... but how far you can escape from it???
[Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan] 15/04 | Sidik Nugroho (Malang):
Kalau aku, dengan yang namanya "bajakan" jadi pusing! Dulu, dengan tegas aku dan seorang teman mengatakan "Stop Pembajakan!" melalui karya yang kami terbitkan dalam kording (koran dinding). Kordingnya sendiri sekarang kolaps karena redaksinya pada menghilang semua, dan nggak ada yang mau mbajak kording kami, padahal kami berharap dibajak lho, karena kording itu kami edarkan gratis di kampus dan sekolah-sekolah!
Memang, realita ini telah menjadi dilema. Kita dibuat jadi serba salah. Siapa sih yang tahan untuk tidak nonton film The Passion? Di gerejaku, VCD bajakannya dijual sama guru-guru Sekolah Minggu untuk cari dana. Wah, "berdosa" sekali tuh guru-guru (kalau kita uuaanti pembajakan). Aku hanya diam dan tidak bisa ngomong apa-apa waktu ngeliat VCD itu laris manis kaya' kacang goreng. Orang Malang berkata: Yok opo maneh? (Bagaimana lagi?). Apakah aku harus teriak: "Stop, jangan beli! Ini Pembajakan!" Hm, kuakui aku bukan Elia dalam industri entertainment.
Sedapat mungkin, aku tidak mengkunsumsi produk bajakan karena kualitasnya biasanya buruk. Namun, dalam hal ini, aku rasa yang paling tepat adalah film bukan cd-program, buku terjemahan atau produk lain. Aku lebih suka nonton yang orisinil. Di Malang, kotaku, rata-rata nyewa 1 film orisinil harganya sekitar Rp. 2000 s/d Rp. 5000. Entahlah bila di tempat lain. Untuk produk selain film, aku sepakat dengan DenMas Marto untuk meminimalisasi (atau "meminimalkan" yang betul Bahasa Indonesia-nya?) pemakaiannya.
Oya, DenMas Marto pernah menulis renungan berjudul "Tidak Usah Malu" dan aku pun tidak malu mengemukakan pendapat akhirku melalui tulisan ini walaupun kurasa dangkal Lha, yok opo maneh… aku sudah merenung-renung, tapi tetap nggak nemu solusinya yang mendalam!
Aku ingin mengajak kita untuk berpulang pada kesadaran masing-masing. Bukankah tidak semua dari kita terpanggil menjadi jurkam anti pembajakan? Kita mungkin dapat memikirkan cara-cara yang menurut kita dapat memperbaiki keadaan ini. Tapi, sebagai orang awam aku lebih cenderung untuk berpikir reflektif dan praktis daripada filosofis dan detail. Aku mau mencegah arus pembajakan dengan langkah sederhana: Memulai untuk tidak membeli produk bajakan dan mengajak keluargaku, teman-temanku dan siapapun yang memungkinkan untuk bisa diajak kalau pas ingat ngajak, untuk melakukan hal yang sama. Apakah berpengaruh?
Anggaplah DenMas Marto sebagai J.R.R Tolkien yang masih hidup dan di tahun ini aku merilis bukunya yang berjudul "The Fellowship of the Swords" (TFotS). Karya-karyanya laris manis, kayak peyek! Namun, setelah diteliti rupanya jumlah karya orisinil yang terjual ternyata kalah jauh bandingannya dengan yang bajakan. Hm, peyek bajakannya rupanya lebih laris (hehe.. emang ada peyek bajakan?). Tolkien, eh, DenMas akan kecewa. Susah-susah beliau membuatnya dan ternyata… huh!
Kini, anggaplah si A yang menjadi pembeli salah satu buku bajakan TFotS. Andaikan ia sadar sebelum membeli (karena ajakanku, ehm) bahwa tindakannya tidak baik, bukankah ia telah mengurangi angka pembelian TFotS bajakan, walaupun hanya sebuah? Ah, apakah artinya sebuah? Jangan anggap enteng! Sebuah bisa ada di mana-mana.
"Whoever saves one man, save the world entire" kata Talmut Yahudi yang jadi semboyan film favoritku: Schindler's List. Hal yang sama bagi pembajakan: "Whoever saves (by not buy) one book (bajakan), save the book (orisinil) entire."
Benarkah demikian?
Kesimpulannya….
Aku tidak menyetujui pembajakan sebuah produk. Ketidaksetujuan itu aku lakukan
dengan: [Kembali ke Atas] [Kirim
Tanggapan]
©
2004 Denmas Marto
Pengalaman Pahit Dibajak dan Memakai Produk Bajakan